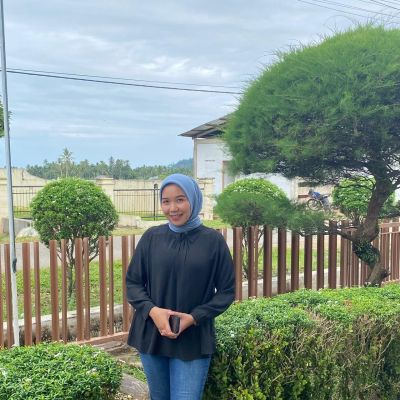Pembelajaran dari Sistem Pemasyarakatan Pennsylvania bagi Reformasi Sistem Pemasyarakatan Indonesia

Rey Hafidz Riamizard
SIGAPNEWS.CO.ID | PADANG -- Oleh Rey Hafidz Riamizard, Penuis adalah Magister Hukum Universitas Andalas
Sistem pemasyarakatan merupakan subsistem penting dalam sistem peradilan pidana yang berfungsi sebagai instrumen negara dalam melaksanakan tujuan pemidanaan, cara suatu negara merancang dan mengelola sistem pemasyarakatan pada dasarnya mencerminkan cara pandang negara tersebut terhadap pelaku tindak pidana, apakah diposisikan semata-mata sebagai objek penghukuman atau sebagai subjek hukum yang masih memiliki martabat dan potensi untuk diperbaiki.
Dalam perkembangan pemikiran hukum pidana modern, pemidanaan tidak lagi dipahami secara tunggal sebagai sarana pembalasan, melainkan sebagai mekanisme sosial yang bertujuan mendorong perubahan perilaku dan mempersiapkan pelaku tindak pidana untuk kembali hidup bermasyarakat secara bertanggung jawab.
Sejarah pemidanaan menunjukkan bahwa sistem kepenjaraan pada awalnya dibangun dengan orientasi represif dan punitif. Penjara dipahami sebagai ruang isolasi dan penderitaan, dimana pencabutan kemerdekaan dipandang sebagai inti dari hukuman itu sendiri. Dalam sistem kepenjaraan klasik, tidak terdapat perhatian yang memadai terhadap aspek pembinaan narapidana maupun dampak sosial dari pemenjaraan. Pola demikian kemudian melahirkan kritik karena dinilai tidak efektif dalam menekan angka kejahatan serta menimbulkan berbagai persoalan kemanusiaan.
Kritik terhadap sistem kepenjaraan inilah yang mendorong lahirnya berbagai model pemasyarakatan alternatif, termasuk sistem Pemasyarakatan Pennsylvania (Pennsylvanian System) yang berkembang di Amerika Serikat pada awal abad ke-19. Pennsylvanian System dibangun atas asumsi bahwa, kejahatan merupakan akibat dari kegagalan moral individu. Oleh karena itu, sistem ini menekankan isolasi individual terhadap narapidana dengan tujuan mendorong refleksi diri, penyesalan, dan pertobatan melalui kesendirian.
Pada konteks historisnya, pendekatan ini dipandang progresif karena berupaya meninggalkan praktik hukuman fisik yang kejam dan menggantikannya dengan metode yang dianggap lebih beradab. Namun, dalam perkembangannya, sistem isolasi total tersebut justru menimbulkan dampak psikologis yang serius dan dinilai bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia. Pengalaman historis ini menunjukkan bahwa, pemasyarakatan yang hanya menitikberatkan pada pengendalian individu tanpa memperhatikan dimensi sosial dan kemanusiaan berpotensi gagal mencapai tujuan pemidanaan secara substantif.
Dalam konteks Indonesia, praktik pemidanaan pada masa kolonial hingga awal kemerdekaan juga masih sangat dipengaruhi oleh paradigma kepenjaraan yang represif. Penjara berfungsi terutama sebagai sarana penghukuman dan pengendalian, sementara narapidana diposisikan sebagai objek kekuasaan negara. Perubahan paradigma mulai diperkenalkan ketika konsep pemasyarakatan dikembangkan sebagai antitesis terhadap sistem kepenjaraan.
Konsep ini menempatkan narapidana sebagai manusia yang perlu dibina dan dipulihkan relasi sosialnya, bukan semata-mata dijatuhi penderitaan. Secara konseptual, sistem pemasyarakatan Indonesia dibangun atas asas pengayoman dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, dengan tujuan utama membentuk kembali warga binaan agar mampu berintegrasi secara sehat dalam masyarakat . Paradigma tersebut, kemudian dilembagakan secara normatif melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menegaskan bahwa, pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka pembinaan narapidana agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana.
Dengan demikian, lembaga pemasyarakatan tidak lagi dipahami sebagai institusi penghukuman semata, melainkan sebagai sarana pembinaan yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Namun, berbagai kajian menunjukkan bahwa implementasi sistem pemasyarakatan Indonesia masih menghadapi persoalan serius, terutama akibat dominasi pidana penjara dalam praktik peradilan pidana.
Kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan, keterbatasan sarana pembinaan, serta orientasi kebijakan pidana yang masih menempatkan penjara sebagai sanksi utama menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif pemasyarakatan dan realitas empiris. Kondisi tersebut menyebabkan lembaga pemasyarakatan kerap kehilangan fungsi pembinaannya dan cenderung beroperasi sebagai tempat penahanan belaka. Dalam situasi demikian, tujuan rehabilitatif dan reintegratif sulit diwujudkan secara optimal, bahkan berpotensi melahirkan berbagai masalah baru dalam sistem pemasyarakatan.
Berdasarkan kondisi tersebut, kajian mengenai pembelajaran dari Sistem Pemasyarakatan Pennsylvania menjadi relevan untuk merefleksikan arah reformasi sistem pemasyarakatan Indonesia. Perbandingan ini tidak dimaksudkan untuk mengadopsi pendekatan isolatif yang telah terbukti problematik, melainkan untuk memahami batas-batas historis sistem pemasyarakatan berbasis penjara serta merumuskan penguatan kebijakan pemasyarakatan yang lebih humanis, efektif, dan selaras dengan tujuan pemidanaan modern.
Karakteristik dan Tujuan Sistem Pemasyarakatan Indonesia
Sistem Pemasyarakatan Pennsylvania (Pennsylvanian System) merupakan salah satu model awal pemasyarakatan modern yang lahir sebagai respons terhadap praktik pemidanaan yang bersifat brutal dan tidak manusiawi pada akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19. Sistem ini dibangun atas keyakinan bahwa, kejahatan pada dasarnya merupakan akibat dari kegagalan moral individu. Oleh karena itu, pemasyarakatan dipahami sebagai proses pembentukan kembali kesadaran moral melalui refleksi diri dan pertobatan. Narapidana ditempatkan dalam sel individual dengan pembatasan interaksi sosial secara ketat, dengan asumsi bahwa kesendirian akan mendorong introspeksi dan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik.
Dalam perspektif historis, Pennsylvanian System dipandang sebagai upaya awal untuk melakukan humanisasi pemidanaan. Sistem ini berusaha meninggalkan hukuman fisik yang kejam, seperti cambukan dan kerja paksa, yang sebelumnya menjadi ciri utama sistem kepenjaraan klasik. Pencabutan kemerdekaan tidak lagi disertai penderitaan fisik secara langsung, melainkan diarahkan pada penderitaan psikologis yang dianggap mampu menumbuhkan kesadaran moral. Dengan demikian, sistem ini merepresentasikan pergeseran awal dari pemidanaan yang bersifat represif menuju pendekatan yang lebih reflektif dan moralistik.
Namun demikian, dalam perkembangannya, penerapan isolasi individual secara total justru menimbulkan berbagai persoalan serius. Isolasi berkepanjangan terbukti berdampak negatif terhadap kondisi psikologis narapidana, seperti gangguan kecemasan, depresi, dan hilangnya kemampuan bersosialisasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan pemasyarakatan yang hanya berfokus pada dimensi moral individual, tanpa mempertimbangkan kebutuhan sosial dan psikologis manusia, mengandung kelemahan struktural. Narapidana sebagai makhluk sosial tidak dapat sepenuhnya dipisahkan dari interaksi manusia tanpa menimbulkan konsekuensi yang merusak tujuan pemidanaan itu sendiri.
Kritik terhadap Pennsylvanian System juga menunjukkan bahwa, pemasyarakatan tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial yang lebih luas. Upaya perubahan perilaku tidak hanya ditentukan oleh refleksi individu, tetapi juga oleh proses interaksi sosial, pembelajaran, dan dukungan lingkungan. Oleh karena itu, sistem isolasi total dinilai gagal mempersiapkan narapidana untuk kembali hidup bermasyarakat setelah menjalani pidana. Dalam konteks ini, Pennsylvanian System lebih mencerminkan pendekatan pemidanaan yang bersifat individualistik dan ahistoris, karena mengabaikan faktor sosial sebagai bagian integral dari proses reintegrasi.
Pengalaman historis tersebut menjadi penting sebagai bahan refleksi dalam pengembangan sistem pemasyarakatan modern. Kritik terhadap Pennsylvanian System memperlihatkan bahwa, tujuan pemasyarakatan tidak dapat dicapai hanya dengan menekankan pertobatan moral individual, tetapi harus diimbangi dengan pembinaan sosial yang memungkinkan narapidana membangun kembali relasi dengan masyarakat. Dengan demikian, kegagalan sistem ini bukan terletak pada niat humanisasinya, melainkan pada keterbatasan pendekatannya yang terlalu sempit dan tidak berkelanjutan.
Pembahasan mengenai karakteristik dan tujuan sistem pemasyarakatan pennsylvania menjadi relevan dalam konteks perbandingan dengan sistem pemasyarakatan Indonesia. Sistem ini memberikan pelajaran historis bahwa, reformasi pemasyarakatan harus memperhatikan keseimbangan antara pembinaan individu dan dimensi sosial pemidanaan. Tanpa keseimbangan tersebut, sistem pemasyarakatan berisiko kehilangan efektivitasnya dan justru melahirkan persoalan baru yang bertentangan dengan tujuan pemidanaan modern.
Perjalanan Sistem Pemasyarakatan Indonesia sebelum Pendekatan Rehabilitatif dan Reintegratif
Sebelum diperkenalkannya konsep sistem pemasyarakatan sebagaimana dikenal dalam kerangka hukum positif Indonesia saat ini, praktik pemidanaan di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh sistem kepenjaraan (prison system) warisan kolonial Belanda. Dalam sistem tersebut, penjara diposisikan terutama sebagai instrumen penghukuman dan pengendalian sosial, bukan sebagai sarana pembinaan. Narapidana dipandang sebagai objek hukuman yang harus dipisahkan dari masyarakat demi menjaga ketertiban umum, dengan penekanan pada pencabutan kemerdekaan, penderitaan fisik, serta disiplin yang keras sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan pidana yang dilakukan.
Orientasi utama sistem kepenjaraan kolonial bersifat retributif dan represif. Penjara tidak dirancang untuk mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat, melainkan untuk menciptakan efek jera melalui kondisi hidup yang berat dan pembatasan hak secara ketat. Dalam konteks ini, pemidanaan lebih berfungsi sebagai sarana penegasan kekuasaan negara daripada sebagai instrumen perbaikan sosial. Pola demikian menunjukkan bahwa sistem kepenjaraan kolonial mengabaikan dimensi kemanusiaan narapidana serta tidak memiliki visi jangka panjang terkait reintegrasi sosial pasca-pidana.
Pasca kemerdekaan, praktik pemidanaan di Indonesia pada tahap awal belum mengalami perubahan yang signifikan. Sistem kepenjaraan kolonial pada dasarnya masih dipertahankan, baik dari segi kelembagaan maupun orientasi pemidanaannya. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan sumber daya negara yang baru merdeka, belum terbentuknya kerangka hukum nasional yang komprehensif, serta kuatnya warisan paradigma kolonial dalam sistem peradilan pidana. Akibatnya, penjara masih dipahami sebagai tempat menjalani hukuman semata, sementara aspek pembinaan narapidana belum menjadi perhatian utama kebijakan pemidanaan.
Perubahan paradigma mulai tampak pada awal dekade 1960-an dengan diperkenalkannya konsep pemasyarakatan oleh Sahardjo, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman. Gagasan pemasyarakatan menandai pergeseran mendasar dalam cara pandang terhadap narapidana, dari “penjahat yang harus dihukum” menjadi “manusia yang tersesat dan perlu dibina”. Dalam konsepsi ini, narapidana dipandang sebagai bagian dari masyarakat yang untuk sementara waktu kehilangan kemerdekaannya, namun tetap memiliki hak asasi dan potensi untuk diperbaiki. Pemasyarakatan tidak lagi dimaknai sebagai penghukuman semata, melainkan sebagai proses sosial untuk memulihkan hubungan antara individu, masyarakat, dan negara.
Transformasi tersebut kemudian memperoleh legitimasi normatif melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang ini secara tegas mengukuhkan pendekatan rehabilitatif dan reintegratif sebagai tujuan utama sistem pemasyarakatan Indonesia. Lembaga pemasyarakatan tidak lagi diposisikan sebagai institusi penghukuman, melainkan sebagai sarana pembinaan yang bertujuan membentuk warga binaan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan mampu kembali berperan secara bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat.
Meskipun secara normatif Indonesia telah meninggalkan pendekatan kepenjaraan yang represif, jejak paradigma lama masih dapat ditemukan dalam praktik pemasyarakatan hingga saat ini. Dominasi pidana penjara sebagai sanksi utama dalam praktik peradilan pidana, kondisi lembaga pemasyarakatan yang mengalami kelebihan kapasitas, serta keterbatasan program pembinaan menunjukkan adanya ketegangan antara tujuan rehabilitatif-reintegratif dan realitas implementasi. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa, perubahan sistem pemasyarakatan tidak hanya membutuhkan reformasi hukum, tetapi juga transformasi struktural dan kultural dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan.
Dengan memahami perjalanan historis sistem pemasyarakatan Indonesia sebelum dan sesudah pengenalan pendekatan rehabilitatif dan reintegratif, sistem pemasyarakatan dapat ditempatkan dalam konteks evolusi pemidanaan yang lebih luas. Dalam kerangka ini, perbandingan dengan Sistem Pemasyarakatan Pennsylvania menjadi relevan bukan untuk mengadopsi metode isolatifnya, melainkan untuk merefleksikan bagaimana setiap sistem pemasyarakatan lahir dari konteks sosial dan filosofi hukum tertentu. Pembelajaran historis tersebut penting untuk memperkuat arah reformasi pemasyarakatan Indonesia agar tidak terjebak pada pengulangan paradigma lama yang secara empiris telah terbukti problematik.
Sistem Pemasyarakatan Indonesia dan Paradigma Reintegratif
Berbeda dengan sistem pemasyarakatan Pennsylvania yang menekankan isolasi individual sebagai sarana pertobatan moral, sistem pemasyarakatan Indonesia dibangun atas dasar paradigma rehabilitatif dan reintegratif. Paradigma ini memandang narapidana bukan, semata-mata sebagai pelaku kejahatan yang harus dihukum, melainkan sebagai subjek hukum yang tetap memiliki hak, martabat, serta potensi untuk diperbaiki. Dalam kerangka ini, pemasyarakatan diarahkan untuk membina narapidana agar,mampu kembali menjalankan fungsi sosialnya secara wajar setelah selesai menjalani pidana.
Paradigma rehabilitatif dan reintegratif tersebut tercermin dalam konsep pembinaan yang menjadi pilar utama sistem pemasyarakatan Indonesia. Pembinaan tidak hanya dimaknai sebagai pengendalian perilaku selama menjalani pidana, tetapi sebagai proses berkelanjutan yang mencakup pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Melalui pembinaan kepribadian, narapidana diarahkan untuk menyadari kesalahan, membangun sikap mental yang lebih positif, serta menanamkan nilai-nilai tanggung jawab sosial. Sementara itu, pembinaan kemandirian bertujuan membekali narapidana dengan keterampilan dan kemampuan praktis yang dapat digunakan sebagai modal sosial dan ekonomi ketika kembali ke masyarakat.
Secara normatif, pendekatan tersebut sejalan dengan nilai-nilai pancasila, khususnya prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem pemasyarakatan Indonesia juga secara konseptual mengadopsi prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia, dengan menempatkan pembatasan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan yang sah dalam pelaksanaan pidana. Dengan demikian, lembaga pemasyarakatan idealnya tidak menjadi ruang penderitaan tambahan, melainkan sarana pembinaan yang memungkinkan terwujudnya reintegrasi sosial secara bermakna.
Namun demikian, berbagai kajian menunjukkan bahwa implementasi paradigma reintegratif tersebut masih menghadapi tantangan struktural yang serius. Salah satu persoalan utama adalah kondisi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan yang disebabkan oleh dominasi pidana penjara dalam praktik peradilan pidana. Overcrowding tidak hanya berdampak pada kondisi fisik lembaga pemasyarakatan, tetapi juga menghambat pelaksanaan program pembinaan secara efektif. Dalam situasi demikian, pembinaan cenderung bersifat administratif dan formalistik, sehingga sulit mencapai tujuan rehabilitatif yang diharapkan. Selain masalah kelebihan kapasitas, keterbatasan jumlah dan kualitas petugas pembina juga menjadi kendala dalam implementasi paradigma reintegratif. Rasio petugas dan narapidana yang tidak seimbang menyebabkan proses pembinaan tidak dapat dilakukan secara individual dan berkelanjutan.
Akibatnya, lembaga pemasyarakatan lebih berfokus pada aspek keamanan dan pengendalian, daripada pada pembinaan yang bersifat transformatif. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara tujuan normatif sistem pemasyarakatan dan realitas pengelolaan lembaga pemasyarakatan di lapangan. Kesenjangan antara konsep dan praktik tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan paradigma rehabilitatif dan reintegratif tidak hanya bergantung pada rumusan normatif, tetapi juga pada kebijakan pemidanaan secara keseluruhan.
Selama pidana penjara masih menjadi sanksi utama yang digunakan secara luas, lembaga pemasyarakatan akan terus dibebani peran yang melampaui kapasitas idealnya. Oleh karena itu, penguatan sistem pemasyarakatan Indonesia memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk reorientasi tujuan pemidanaan, pengembangan alternatif pemidanaan, serta pelibatan masyarakat dalam proses reintegrasi sosial narapidana.
Dalam konteks perbandingan dengan sistem pemasyarakatan pennsylvania, paradigma reintegratif Indonesia menunjukkan arah yang lebih selaras dengan prinsip hukum pidana modern dan hak asasi manusia. Namun, tantangan implementasi yang dihadapi memperlihatkan bahwa, keberhasilan sistem pemasyarakatan tidak hanya ditentukan oleh pilihan paradigma, melainkan juga oleh konsistensi kebijakan dan dukungan struktural dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, reformasi sistem pemasyarakatan Indonesia harus diarahkan tidak hanya pada penguatan norma, tetapi juga pada perbaikan kondisi faktual yang memungkinkan paradigma reintegratif dijalankan secara efektif.
Pembelajaran dari Sistem Pemasyarakatan Pennsylvania
Meskipun sistem pemasyarakatan Pennsylvania (Pennsylvanian System) secara umum telah ditinggalkan dan tidak lagi dianggap relevan untuk diterapkan secara utuh dalam sistem pemasyarakatan modern, pengalaman historis sistem tersebut tetap menyimpan sejumlah pembelajaran penting. Pennsylvanian System menunjukkan bahwa, sejak awal perkembangan pemasyarakatan modern, telah muncul kesadaran bahwa pemidanaan tidak semata-mata bertujuan menghukum secara fisik, melainkan juga diarahkan pada perubahan moral dan perilaku individu. Dalam konteks ini, sistem tersebut menegaskan pentingnya dimensi kesadaran moral dan tanggung jawab pribadi sebagai bagian dari proses pemasyarakatan.
Salah satu pembelajaran utama dari Pennsylvanian System adalah penekanannya pada refleksi diri sebagai sarana perubahan perilaku. Isolasi individual dirancang untuk mendorong narapidana melakukan introspeksi atas kesalahan yang dilakukan, sehingga pemidanaan dipahami sebagai proses perenungan moral, bukan sekadar penderitaan fisik. Meskipun pendekatan isolatif ini terbukti problematik, gagasan dasarnya menunjukkan bahwa pembinaan narapidana tidak dapat dilepaskan dari upaya membangun kesadaran internal mengenai tanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan. Kesadaran semacam ini merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan proses rehabilitasi dalam jangka panjang. Selain itu, Pennsylvanian System juga memperlihatkan pentingnya struktur, disiplin, dan keteraturan dalam penyelenggaraan pemasyarakatan. Sistem ini dirancang dengan tata kelola yang ketat dan konsisten, sehingga pelaksanaan pidana tidak berlangsung secara sewenang-wenang.
Dalam perspektif pemasyarakatan modern, pembelajaran ini menunjukkan bahwa pembinaan narapidana memerlukan kerangka institusional yang jelas dan terarah. Tanpa struktur yang konsisten, program pembinaan berpotensi kehilangan arah dan berubah menjadi rutinitas administratif yang tidak berdampak substantif terhadap perubahan perilaku narapidana .Namun demikian, pengalaman Pennsylvanian System juga memberikan pelajaran penting mengenai batas-batas pendekatan pemasyarakatan yang terlalu menekankan aspek individual dan moralistik. Isolasi total yang diterapkan terbukti mengabaikan hakikat manusia sebagai makhluk sosial, sehingga justru menimbulkan dampak psikologis yang serius dan menghambat kemampuan narapidana untuk kembali berinteraksi secara sehat dengan masyarakat. Kegagalan tersebut menunjukkan bahwa pemasyarakatan tidak dapat dilepaskan dari dimensi sosial, karena proses reintegrasi pada dasarnya merupakan proses membangun kembali relasi antara individu, masyarakat, dan negara.
Dalam konteks sistem pemasyarakatan Indonesia, pembelajaran dari Pennsylvanian Sistem harus ditempatkan secara kritis dan kontekstual. Isolasi total jelas tidak dapat diterima dalam kerangka hak asasi manusia modern dan bertentangan dengan paradigma rehabilitatif dan reintegratif yang dianut Indonesia. Namun demikian, nilai-nilai seperti refleksi diri, evaluasi perilaku, dan pembinaan mental tetap memiliki relevansi apabila diintegrasikan secara lebih humanis dan partisipatif. Pembinaan mental dan moral dapat dilakukan melalui pendekatan konseling, pendidikan, dan pembinaan kepribadian yang tidak menghilangkan interaksi sosial, tetapi justru mempersiapkan narapidana untuk kembali hidup bermasyarakat.
Lebih jauh, pembelajaran dari Pennsylvanian sistem juga mengingatkan bahwa kegagalan pemasyarakatan sering kali bukan semata-mata disebabkan oleh niat atau tujuan sistem tersebut, melainkan oleh pendekatan yang tidak seimbang. Sistem pemasyarakatan yang terlalu menekankan kontrol dan pengendalian individu berpotensi kehilangan tujuan rehabilitatifnya. Dalam hal ini, pengalaman Pennsylvania menjadi peringatan historis bagi sistem pemasyarakatan Indonesia agar tidak terjebak pada pengulangan paradigma sempit, baik dalam bentuk isolasi ekstrem maupun pemenjaraan massal yang mengabaikan kualitas pembinaan. Dengan demikian, pembelajaran dari Sistem Pemasyarakatan Pennsylvania bagi Indonesia terletak bukan pada adopsi model atau metode yang bersifat teknis, melainkan pada pemahaman kritis terhadap tujuan pemasyarakatan itu sendiri.
Reformasi sistem pemasyarakatan Indonesia harus mampu mengambil nilai reflektif dan kedisiplinan dari pengalaman historis tersebut, sekaligus menghindari pendekatan yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan kebutuhan reintegrasi sosial. Pendekatan yang seimbang antara pembinaan individu dan dimensi sosial menjadi kunci agar sistem pemasyarakatan benar-benar berfungsi sebagai sarana pembentukan kembali warga negara yang bertanggung jawab.
Implikasi bagi Reformasi Sistem Pemasyarakatan Indonesia
Reformasi sistem pemasyarakatan Indonesia pada dasarnya tidak dapat hanya dipahami sebagai upaya teknis untuk mengatasi persoalan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan atau peningkatan sarana dan prasarana semata. Reformasi yang bersifat substantif harus diarahkan pada penguatan kualitas pembinaan narapidana, sehingga tujuan rehabilitatif dan reintegratif yang dianut secara normatif benar-benar tercapai dalam praktik. Dalam konteks ini, pembelajaran dari Sistem Pemasyarakatan Pennsylvania memberikan perspektif penting mengenai risiko kegagalan pemasyarakatan apabila aspek sosial dan kemanusiaan diabaikan.
Pengalaman historis Pennsylvanian System menunjukkan bahwa pendekatan pemasyarakatan yang terlalu menitikberatkan pada pembinaan moral individual secara tertutup, tanpa dukungan relasi sosial yang sehat, justru berpotensi menghasilkan dampak kontraproduktif. Isolasi ekstrem yang diterapkan dalam sistem tersebut menghambat kemampuan narapidana untuk membangun kembali keterampilan sosial yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Pelajaran ini relevan bagi Indonesia, terutama dalam menghadapi kecenderungan pemasyarakatan yang masih berorientasi pada pengendalian dan keamanan, sehingga mengesampingkan kualitas interaksi sosial dalam proses pembinaan. Implikasi penting bagi reformasi sistem pemasyarakatan Indonesia adalah perlunya keseimbangan antara pembinaan moral individu dan reintegrasi sosial berbasis masyarakat. Pembinaan kepribadian tetap diperlukan untuk membangun kesadaran hukum, tanggung jawab, dan perubahan sikap mental narapidana. Namun, pembinaan tersebut harus dilengkapi dengan mekanisme yang memungkinkan narapidana tetap terhubung dengan lingkungan sosialnya secara bertahap dan terkontrol. Program asimilasi, pembebasan bersyarat, serta keterlibatan keluarga dan masyarakat merupakan instrumen penting dalam mewujudkan reintegrasi sosial yang efektif.
Selain itu, reformasi pemasyarakatan juga menuntut reorientasi kebijakan pemidanaan secara lebih luas. Selama pidana penjara masih menjadi sanksi utama yang digunakan secara dominan, lembaga pemasyarakatan akan terus dibebani peran yang tidak sebanding dengan kapasitas pembinaan yang tersedia. Dalam situasi demikian, tujuan rehabilitatif cenderung tereduksi menjadi sekadar retorika normatif. Oleh karena itu, pengembangan alternatif pemidanaan non-pemenjaraan, seperti pidana kerja sosial, pidana pengawasan, dan mekanisme keadilan restoratif, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari agenda reformasi sistem pemasyarakatan. Pembelajaran dari Pennsylvanian System juga mengingatkan bahwa reformasi pemasyarakatan tidak dapat dilepaskan dari aspek kelembagaan dan sumber daya manusia. Struktur pembinaan yang baik memerlukan petugas pemasyarakatan yang tidak hanya berfungsi sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai pembina dan fasilitator perubahan perilaku. Tanpa peningkatan kapasitas dan profesionalisme petugas, paradigma rehabilitatif dan reintegratif berpotensi mengalami kegagalan implementasi, meskipun telah diatur secara normatif dalam peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, implikasi reformasi sistem pemasyarakatan Indonesia menuntut pendekatan yang komprehensif dan berimbang. Reformasi tidak boleh terjebak pada pengulangan kesalahan historis sistem pemasyarakatan yang menekankan kontrol berlebihan, sebagaimana tercermin dalam Pennsylvanian System. Sebaliknya, reformasi harus diarahkan pada pembangunan sistem pemasyarakatan yang mampu memadukan pembinaan moral individu, perlindungan hak asasi manusia, dan penguatan peran masyarakat dalam proses reintegrasi sosial. Pendekatan semacam ini menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya sistem pemasyarakatan yang tidak hanya efektif secara hukum, tetapi juga adil dan berkelanjutan secara sosial.
Perbandingan antara Sistem Pemasyarakatan Pennsylvania dan sistem pemasyarakatan Indonesia menunjukkan bahwa, setiap model pemasyarakatan lahir dari konteks sosial, historis, dan filosofi hukum yang berbeda. Pennsylvanian System muncul sebagai respons atas praktik pemidanaan yang brutal pada masanya, dengan membawa gagasan pembinaan moral melalui refleksi diri dan disiplin yang ketat. Namun, pengalaman historis juga memperlihatkan bahwa pendekatan isolatif yang meniadakan dimensi sosial manusia justru menimbulkan persoalan baru dan bertentangan dengan prinsip kemanusiaan serta hak asasi manusia.
Sementara itu, sistem pemasyarakatan Indonesia secara normatif telah mengalami pergeseran paradigma yang signifikan, dari sistem kepenjaraan yang represif menuju pendekatan rehabilitatif dan reintegratif. Melalui konsep pemasyarakatan, narapidana ditempatkan sebagai subjek hukum yang harus dibina dan dipersiapkan untuk kembali ke masyarakat. Pergeseran ini mencerminkan komitmen negara untuk menjadikan pemidanaan sebagai sarana perbaikan sosial, bukan sekadar instrumen pembalasan. Namun demikian, kajian ini menunjukkan bahwa kesenjangan antara tujuan normatif dan realitas implementasi masih menjadi persoalan mendasar dalam praktik pemasyarakatan Indonesia.
Pembelajaran dari Sistem Pemasyarakatan Pennsylvania menegaskan bahwa, keberhasilan pemasyarakatan tidak dapat dicapai melalui penekanan sepihak pada aspek moral individual atau pengendalian semata. Pemasyarakatan yang mengabaikan dimensi sosial dan psikologis berpotensi gagal mencapai tujuan rehabilitasi dan bahkan memperburuk kondisi narapidana. Oleh karena itu, pembinaan moral dan kedisiplinan hanya akan efektif apabila ditempatkan dalam kerangka yang menghormati hak asasi manusia serta mendukung proses reintegrasi sosial secara bertahap dan berkelanjutan.
Implikasi utama bagi reformasi sistem pemasyarakatan Indonesia adalah perlunya pendekatan yang lebih berimbang dan komprehensif. Reformasi tidak cukup dilakukan melalui perubahan regulasi atau peningkatan kapasitas fisik lembaga pemasyarakatan, tetapi harus menyentuh kebijakan pemidanaan secara menyeluruh, kualitas pembinaan, serta peran masyarakat dalam proses reintegrasi sosial. Tanpa reorientasi tersebut, sistem pemasyarakatan berisiko terjebak pada pengulangan pola lama yang bersifat administratif dan represif, meskipun secara normatif mengusung paradigma rehabilitatif.
Dengan demikian, perbandingan antara Sistem Pemasyarakatan Pennsylvania dan sistem pemasyarakatan Indonesia tidak dimaksudkan untuk mencari model yang dapat diadopsi secara langsung, melainkan untuk memahami batas-batas historis dan filosofis dari setiap pendekatan pemasyarakatan. Pemahaman kritis terhadap pengalaman masa lalu menjadi penting agar reformasi sistem pemasyarakatan Indonesia dapat diarahkan pada penguatan nilai kemanusiaan, efektivitas pembinaan, dan keberlanjutan reintegrasi sosial. Hanya dengan pendekatan yang demikian, sistem pemasyarakatan dapat benar-benar berfungsi sebagai instrumen keadilan yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan.(*)
Editor :Andry